
Gelap terangnya Sawahlunto, jaya dan terpuruknya, duka dan tawa penduduknya selama seratusan tahun, ditentukan oleh batu bara yang bersemayam di bawah tanahnya. Dari Sawahlunto, rel dibangun, stasiun-stasiun berdiri, silo-silo tegak, dan pelabuhan tercipta. Peradaban baru masuk di tengah Sumatra yang ketika itu masih gelap. Dari para pesakitan yang menggali lubang-lubang tambang, mesin-mesin di negara industri digerakkan. Dari orang-orang hukuman yang mendorong lori-lori penuh emas hitam, bahasa baru lahir, dan pemberontakan atas penindasan dan keterjajahan juga lahir. Betapa, nasionalisme kadang lahir dari tempat yang tidak terduga: lubang tambang!
Kini, masa tambang telah lama usai. Bagai bangkai-bangkai dari zaman revolusi industri, silo-silo penuh karat, rel dan stasiun yang ditelantarkan oleh waktu dan lekang oleh udara tropis—semua tinggal dalam cerita, dalam catatan sejarah, lakon-lakon wayang, dan ingatan yang setengah buram. Ombilin, Sawahlunto, mewariskan begitu banyak hal yang tidak semata yang terlihat, bukan?
Silo Gunung di pangkal Teluk Bayur, tempat pengumpulan batu bara sebelum dikapalkan ke negara-negara industri, kini terkangkang tak berdaya digerayangi zaman.
Bagai museum saja ia teronggok di situ. Bangunan-bangunan uzur berwarna kusam, kait besi yang berkarat, derek bunker listrik yang dianggap memakai teknologi tinggi paling mutakhir di masanya itu, kini, bagai bangkai-bangkai yang datang dari masa lalu yang jauh. Besi-besi raksasa setengah menghitam yang tertancap begitu tinggi dikuasai lumut, roda-roda besi bekas kereta atau lori yang penuh karat dihajar hujan dan panas musim, dan gedung beton panjang yang sendirian dengan segenap kesunyian lorong-lorongnya—sebuah interpretasi dari sunyinya dunia sebelum revolusi industri.
Berdiri pada bahu salah satu bangunan, menghadap ke barat, terlihat pelabuhan yang dulu bernama Emma Haven, dengan laut biru membentang dan kapal-kapal beragam ukuran tengah melego jangkar. Pelabuhan yang kini tidak begitu menggembirakan. Sesekali, gerbong-gerbong kereta yang mengangkut semen dari Indarung mendengus di rel yang menuju pelabuhan. Praktis hanya, kereta semen yang masih beroperasi, kata penjaga palang pintu kereta Teluk Bayur pada 20 November 2023. Sementara, rel-rel itu, bila ditelusuri, akan berhulu lebih jauh nun ke pedalaman Minangkabau, ke Sawahlunto. Alasan kuat yang membuat semua ini ada, silo ini, jalur kereta, stasiun-stasiun, juga pelabuhan besar itu.
Kisahnya, setidaknya, bermula dari dua orang insinyur Belanda. C. de Groot menyusuri Singkarak pada pertengahan abad ke-19 dan disusul W. H. de Grave yang berakit di Sungai Ombilin hampir dua puluh tahun setelah itu. Hasil hipotesa keduanya menggembirakan sekaligus mencengangkan: ratusan juta ton emas hitam bersemayam di sekitar Lembah Lunto. Revolusi industri yang panjang di Eropa tengah menggeser peradaban. Dan dunia butuh energi untuk menggerakkan mesin-mesin industri: batu bara!
Keinginan mengeksploitasi timbul dari pemerintah kolonial Belanda. Tapi memakai tenaga alat angkut apa?
Hanya dalam beberapa dekade saja setelah kedatangan insinyur itu, mesin dan lori didatangkan ke Sawahlunto. Jalur kereta yang pada awalnya direncanakan untuk mengangkut kopi dari dataran tinggi Minangkabau, diubah. Begitu dicatat Rusli Amran dalam Sumatera Barat hingga Plakat Panjang. Pembangunan yang ambisius itu dipercepat. Rel dibuat hingga ke pelabuhan Emma Haven (Teluk Bayur) di pesisir pantai barat Sumatra. Lorong-lorong penggalian batu bara Ombilin tercipta. Silo-silo untuk menampung batu bara dibangun menjulang tinggi. Dan tentu saja, beribu-ribu pekerja tambang didatangkan sebagai kaki dan tangan industri.
Pada mulanya pekerja diangkut dari Penjara Muara Padang, penjara kolonial yang memang terkenal sebagai pusat pemenjaraan bagi tahanan hukuman berat (Centrale Gevanenis voor Strafgevangenis) sejak awal abad ke-19. Tapi kebutuhan akan pekerja tidak sebanding dengan jumlah tahanan yang ‘tersedia’ di penjara itu. Pemerintah Belanda kemudian juga mendatangkan narapidana dari penjara di Cipinang dan Glodok di Batavia. Beberapa dari tahanan yang dianggap berbahaya dikalungkan rantai besi yang melingkari pegelangan tangan dan kaki mereka. Pada tahun 1896 lebih dari seribu kuli dipekerjakan paksa. Ahli sejarah menyebut mereka kettingganger atau ”urang rantai” dalam bahasa pribumi setempat, orang-orang yang tangan dan kaki mereka dirantai.
Marah Rusli menggambarkan dengan sangat hidup satu potongan dari kisah kedatangan tahanan yang akan dikirim ke “gulag” Sawahlunto itu dalam roman Sitti Nurbaya. Di Teluk Bayur, tulis Rusli, ada seorang tahanan dalam kapal dengan tangan terikat rantai. Dengan wajah putus asa, lelaki itu melompat ke dalam laut dan tidak timbul lagi. Syamsul Bahri, tokoh utama roman awal abad ke-20 itu, yang menyaksikan kejadian itu dengan jantung berdegup kencang menunggu tahanan itu muncul ke permukaan air yang saat itu gelombangnya sangat besar.
“Rupanya karena putus asa, lebih suka ia mati di dalam laut daripada menanggung kesengsaraan, kehinaan, dan malu. Patutlah acap kali hamba lihat ia termenung dan terkadang-kadang menangis di sisi kapal; makan pun kerap tiada suka. Kabarnya ia dipersalahkan membunuh orang, sebab itu dihukum buang dalam rantai lima belas tahun lamanya ke Sawahlunto,” kata Syamsul Bahri, tulis Marah Rusli pula.

Karena tidak cukup juga tenaga kuli dari kalangan narapidana, lowongan kerja kemudian dibuka secara besar-besaran. Dengan sistem kontrak, para kuli didatangkan dari Jawa, Bali, Madura, dan Bugis untuk menggali emas hitam dari perut bumi Sawahlunto. Buruh kontrak Tionghoa juga didatangkan melalui kongsi-kongsi tenaga kerja yang ada di Penang dan Singapura maupun yang dikirim langsung dari daratan Tiongkok. Sedang dari Jawa didatangkan melalui kantor pengerahan tenaga kerja yang ada di Semarang, Batavia, dan Surabaya. Rel kereta sepanjang 155 kilometer tercipta, pelabuhan besar, gudang-gudang, lorong-lorong. Sejarah mencatatnya begitu detil.
Di antara ribuan pekerja tambang itu terdapat perempuan-perempuan yang bertindak sebagai penghibur, baik sebagai ronggeng atau penari tandak atau dalam bahasa kasar disebut pelacur tradisional. Ronggeng, tandak dancers, tulis sejarawan Erwiza Erman dalam Miners, Managers and The State: A Socio-Political History of The Ombilin Coal-Mines,West Sumatra, 1892-1996, menghibur para penambang agar mereka betah tinggal dalam jangka panjang untuk bekerja dengan perusahaan. Para perempuan penghibur ini direkrut selama enam bulan pada suatu waktu, biasanya ketika kontrak kerja para kuli akan habis—semacam ‘rayuan’ agar para kuli memperpanjang kontrak kerjanya.
Para penari itu adalah wanita muda yang cantik, yang juga terikat kontrak kerja. Ketika dua atau tiga tahun bekerja sebagai ‘penari’, perusahaan akan merekrut ‘penghibur’ baru, yang lebih molek, yang lebih muda. Secara umum, beberapa mantan penari itu tidak kembali pulang. Banyak dari mereka memilih tetap di Sawahlunto dan menikah dengan buruh kontrak atau buruh bebas, lalu meninggal di Sawahlunto. Kehadiran penari ronggeng ini, telah pula menjadi perhatian pejabat Belanda dan Inspektur Tenaga Kerja.
Henri Hubertus van Kol, seorang sosialis pertama yang menginjakkan kaki di Hindia Belanda, dalam Uit onze koloniën: Uitvoerig reisverhaal misalnya, mengunjungi Sawahlunto di awal abad ke-20 mencatat adanya 50 kelompok ronggeng penari untuk menghibur para pekerja tambang, yang masing-masing kelompok memiliki beberapa perempuan penari. Van Kol menggambarkan daerah-daerah yang dikunjunginya lengkap berikut streotipe; orang Jawa yang pemalas, orang Ambon yang tidak jujur dan memanjakan diri sendiri. Ia mengkritik praktik perbudakan Hindia Belanda, walau ia sendiri mempekerjakan pribumi miskin di perkebunan kopi miliknya, Cayumas di Jawa Timur.
Sementara, dari daratan Eropa berdatangan para ahli dan mandor—para tuan-tuan perusahaan tambang. Mereka membawa gaya hidup Eropa mereka yang mewah ke pedalaman Minangkabau itu. Dengan dansa-dansi yang hampir saban pekan dipergelarkan di gedung pusat hiburan di kota itu demi untuk mengusir kejenuhan bekerja di medan-medan tambang, pun dengan diskriminasi ras yang mereka pelihara.
Orang-orang dari berbagai kultur telah datang ke Sawahlunto mencari peruntungan atau pun dibawa oleh untungnya sendiri. Kota itu kemudian menciptakan stratifikasi kelas yang rasial: para tuan, pialang, pedagang, hingga kelas paling rendah sebagai pekerja paksa. Mulai dari Eropa, Tionghoa, Batak, Minangkabau, Jawa, hingga Nias. Di lembah aliran Sungai Lunto ini pula berkumpul hampir 11.000 pekerja dengan status yang berbeda-beda, baik sebagai pekerja paksa, kuli kontrak, termasuk buruh lepas asal Minangkabau, Nias, Melayu dan Batak. Dari retak tulang orang rantai, dari keringat asam para pekerja itulah Kota Sawahlunto ada. Dan Sawahlunto kemudian bagai sebuah miniatur Indonesia yang plural. Kesadaran akan ke-bhineka-an tumbuh mempersatukan mereka, nasionalisme barangkali lahir dari tekanan dan rasa ketertindasan.


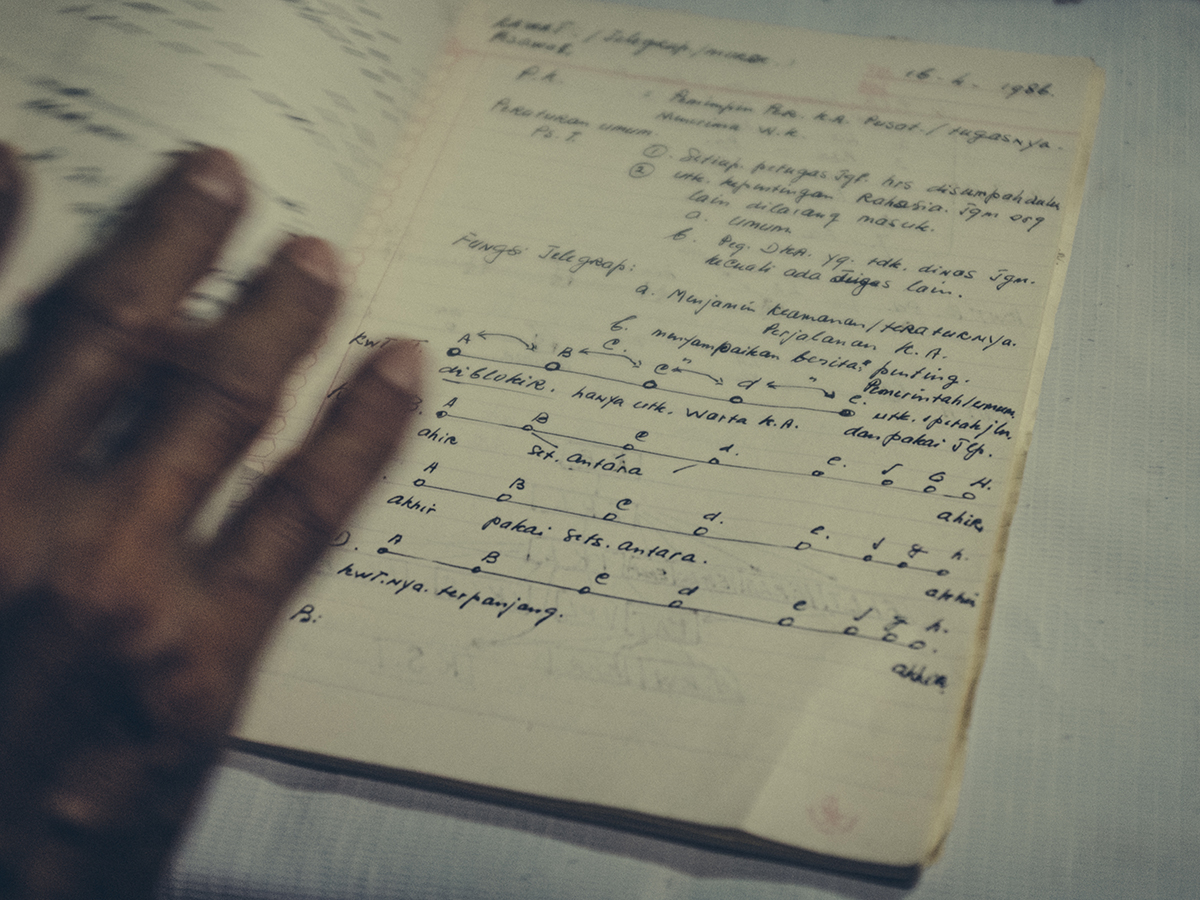

Kesadaran sebagai orang terjajah itulah barangkali yang menyulut api pemberontakan, yang berkobar-kobar pada tahun 1927 di Silungkang, nagari tua Minangkabau yang terletak di pinggiran Kota Sawahlunto. Pemberontakan itu dicatat sebagai pemberontakan yang melibatkan orang-orang dari berbagai kultur. Beberapa pemimpinnya berasal dari orang Minangkabau, Jawa, dan juga Batak. Pemberontakan itu disambut para kuli sampai membunuh beberapa tuan Belanda, dan menyerang Penjara Sawahlunto yang terkenal angker—representasi dari kolonialisme yang hegemonik itu.
Namun, keberagaman ras dan kultur di Sawahlunto tidak hanya sampai di sana. Dari lobang-lobang hitam galian batu bara itu, bahasa baru lahir. Sebuah bahasa hasil dari pencampuran bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Batak, China, Minangkabau, Belanda, dan bahasa Melayu sebagai bahasa dasar. Bahasa Tansi, begitu jenis bahasa baru ini disebut Elsa Putri E.S dalam Menggali Bara Menemu Bahasa. Bahasa Tansi, bahasa kreol (buruh) yang lahir dari perdagangan yang secara geografis berada dan berkembang di wilayah pesisiran, misalnya di Karibia dan Papua New Guinea. Uniknya, Bahasa Tansi (penjara) ini lahir justru bukan di pesisiran, melainkan di pedalaman. Bahasa Tansi Sawahlunto, menurut Elsa, adalah bahasa yang lahir dari percakapan para kuli tambang dari berbagai lintas kultur. Bahasa itu hingga kini masih dapat didengar di Sawahlunto, menyembur dari mulut-mulut warga kotanya dengan lancar.
Lebih dari satu abad, Sawahunto berlimpah kemewahan, bermandikan cahaya. Kota itu telah terang benderang ketika segenap pulau Sumatra masih gelap. Sawahlunto telah mencicipi kemewahan ketika Indonesia masih berkutat pada ketakutan-ketakutan akan kekurangan pangan. Dari Cornell University, sebuah berkala terkenal, Indonesia, pada tahun 2005 pernah menurunkan sebuah artikel yang menuliskan tentang gaya hidup mewah di Sawahlunto.
Susan Rodgers dalam A Nederlander Woman’s Recollections of Colonial and Wartime Sumatra: from Sawahlunto to Bangkinang Internment Camp, menulis tentang keberadaan kolam-kolam pemandian yang terdapat di Muaro Kalaban pada masa kolonial Belanda, mobil-mobil pribadi yang mahal milik para orang kaya kota menyesaki jalan-jalan kota yang lapang dan mulus, juga rumah-rumah bola tempat tuan-tuan kolonial menghibur diri pada akhir pekan. Kemewahan hidup yang berhenti sesaat ketika Jepang datang, tetapi berlanjut kembali hingga setengah abad setelah kekuasaan kolonial hilang dari Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, aktivitas tambang diteruskan pemerintah. Pekerja ditambah, upah dinaikkan, dan perlakuan kasar mandor dihapuskan. Di tengah pedalaman Sumatra yang masih purba, Sawahlunto tumbuh pesat dalam gemerlap kota.
Keluarga Fak Sin Kek, salah satunya, hidup dalam kemewahan itu. “Tak hanya orang Tionghoa, orang Jawa, Sunda, Minang, semua penduduk hidup makmur di sini,” kenang Sudarma yang tinggal di rumah Fak Sin Kek, bangunan tua yang dilabeli sebagai benda Cagar Budaya. Fak Sin Kek, mertua Sudarma, adalah salah seorang saudagar dari negeri Tiongkok yang datang ke Sawahlunto sebagai peternak sapi sekaligus penjual susu untuk para meneer Belanda. “Itu dulu, dulu sekali,” kata Sudarma bercerita di rumahnya suatu siang. Dulu, ketika emas hitam masih dikeruk, ketika lori dan ribuan pekerja masih menggali batu bara dari lorong-lorong panjang di bawah kota.
“Di malam hari, tiap penjuru kota ini diisi pesta. Tiap awal bulan, gelanggang akan menampilkan pementasan musik besar-besaran. Artis-artis kawakan dari ibukota dibawa untuk mengisi panggung hiburan,” Kamsi Benti, perempuan tua yang begitu bersemangat bercerita tentang kotanya. “Kami melihat langsung Bing Slamet bernyanyi,” Gusmarni, pensiunan guru yang juga sudah uzur, mengenang masa remaja yang ia habiskan di kota ini.
Tapi, waktu tidak diam, ia berputar, tahun berjalan laksana laju kereta batu bara yang sesak dan mendengus parau membelah Sumatra yang gelap. Sawahlunto yang bahagia dan bermandi cahaya berubah muram, tiba-tiba. Pada 1995, pamor emas hitam itu mulai redup. Produksi batu bara Ombilin terus merosot tajam seiring dengan mengeringnya batu bara tambang luar, belum lagi harga batu bara anjlok di pasar dunia. PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin yang dikelola pemerintah terus merugi. Entah pengaruh politik yang tengah memanas pada masa itu, atau krisis moneter, PHK besar-besaran diberlakukan, walau dengan tunjangan yang sangat tinggi. Beberapa lokasi tambang ditutup. Sawahlunto kemudian tak ubahnya seperti kota mati dengan serakan bangkai-bangkai besi penuh karat. Perekonomiannya lumpuh. Alasannya tak lain dari batu bara. Emas hitam mengilap yang dulu menggerakkan mesin industri bagai susut dan hilang dari Sawahlunto, batu bara sekaligus kehilangan pamor oleh minyak bumi yang siap menggantikannya. Ombilin, Sawahlunto, ditinggalkan.
Tambang di Ombilin, Sawahlnto yang kemudian menjadikan ekspatriat baru, kelasi baru, tinggal cerita. Kereta yang semula berisi gerbong-gerbong batu bara, ditambah gerbong barang dan penumpang, semua tinggal cerita. Di dekat stasiun Lubuk Alung didirikan pabrik dan gudang kopra, mengingat Pariaman adalah penghasil kelapa terbanyak di Indonesia masa itu, menggantungkan transportasinya pada kereta, kini juga telah tinggal bangunan usang. Di beberapa tempat yang dilalui kereta seperti stasiun Alai, para pandai besi menggunakan batu bara sebagai bahan bakar—batu bara yang tercecer dari gerbong-gerbong penuh batu bara yang melintas. Seiring berhentinya kereta batu bara dan barang melintas, usah-usaha rakyat yang bergantung pada kereta juga tutup usia.
“Tidak ada yang bisa diharap lagi. Di kota ini lebih banyak pedagang dari pada pembeli,” Sudarma mengeluh. Kemudian bibirnya menyunggingkan senyum pahit, dan matanya yang sipit setengah nanar mengenang riwayat kota yang ditempatinya.
“Pada saat itu, banyak yang stres, ada yang jatuh stroke,” ungkap Kamsri Benty, perempuan yang telah mulai uzur namun lincah menilai kotanya di rumahnya di Tansi.
Kehidupan mewah tiba-tiba terdepak oleh agenda penyusutan tenaga kerja. Sawahlunto menjadi senyap seperti ia mula-mula didatangi dua orang insinyur Belanda pada pertengahan abad ke-19 dulu. “Saya tak tahu kenapa saya menangis, o, mungkin saya terlalu berlebihan. Kota yang dulu megah sekarang terasa menakutkan,” tambah Gusmarni.
Reformasi pecah di Jakarta, beratus lubang-lubang tambang marak bermunculan—walau dalam skala kecil—tersebar di pinggir kota. Batu bara memang tidak pernah habis dari bumi Sawahlunto, sesuai perkiraan dua abad silam. Tapi, kejayaan masa lalu adakah yang bisa mengembalikannya?
Dan kini, apa yang tersisa dari semua itu selain cerita?
Stasiun-stasiun itu, jalur kereta yang terentang dari pedalaman Sawahlunto, lobang-lobang galian, silo-silo yang bagai bangkai sejarah, hingga pelabuhannya, pada 6 Juli 2019 silam ditetapkan sebagai warisan dunia. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO menetapkan sebagai Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto, WTBOS.
Menelusuri ruas demi ruas jalur kereta dari Teluk Bayur hingga Sawahlunto bagai menyusun lembaran-lembaran cerita yang tindih menindih. Di Padang, Duku hingga Kayutanam, rel yang sama masih digunakan. Hanya saja tidak ada lagi batu bara yang diangkut. Rel bergigi di bagian tengah yang jamak dijumpai mulai dari Kayutanam hingga Lembah Anai, yang rel-relnya melintang di ketinggian, dan jembatan tinggi yang membuat ngeri. Teknologi yang begitu mutakhir di masanya, yang hanya ada di Swiss dan Sumatra Barat, Ambarawa dan India, rel bergerigi yang populer dikenal dengan Riggenbach System dengan lokomotif bersilinder ganda. Saya menyinggahi stasiun Padang Panjang yang sepi, hingga terus ke Batu Tabal, hendak menyerong ke pinggir Danau Singkarak.
Akhir tahun begini, perhelatan melihat kembali ke warisan tambang ini digelar, salah satunya di Kacang, sebuah nagari di tepi Danau Singkarak. Stasiun yang telah somplak dan rel yang sudah tidak lagi utuh karena tidak lagi dilewati kereta dan beberapa ruas rel telah raib, kembali dibersihkan warganya. Masyarakat berbondong-bondong datang. Stasiun ramai oleh orang, tidak seperti biasanya, kata beberapa orang tua. “Bahkan, orang telah lupa kalau di kampung mereka masih ada stasiun,” kata Firman, warga Kacang yang telah berusia hampir 70 tahun.
Helat Gelanggang Arang namanya, tengah dilangsungkan di beberapa stasiun yang dilewati jalur kereta batu bara masa silam. Tari-tarian yang selama ini tidak pernah lagi dipentaskan, sekarang digelar. Dalam gedung stasiun yang telah usang, dipamerkan foto-foto zaman kolonial; orang-orang rantai, kereta dengan asap melintas dari pedalaman, miniatur kereta batu bara, batu bara. Betapa, semua berakar dari batu bara. Firman melihat dengan mengangguk-anggukan kepala sembari menikmati beragam menu makanan.
Di pentas, para intelektual bicara. “Kita kembalikan kejayaan,” kata Rahmat Gino, salah seorang pengusul WTBOS. Doktor Eka Maryanti, salah satu pembicara pada festival itu menambahkan, dengan bantuan teori ekonomi, lewat pariwisata, semua kejayaan itu mau dikembalikan. Di awal abad ke-21 Sawahlunto telah mencoba menukar arah haluan dari kota tambang yang mendatangkan buruh, menjadi kota wisata yang mengundang turis. Lokomotif uap telah didatangkan kembali, tempat-tempat bersejarah dipugar, festival-festival digelar, dan segala warisan budaya dan sejarah tambang dibincangkan kembali.
“Dulu. Ini dulu ya. Limau Kacang yang terkenal dari Kacang ini, diangkut ke Padang menggunakan kereta. Padang terasa dekat saja,” kata Firman merespon pembicara dari samping saya. Lelaki uzur itu tertawa-tawa melihat foto-foto yang digelar. Ia, katanya, masih mengingat bagaimana kereta lewat di stasiun Kacang, di kampungnya. Bagaimana orang-orang dari Kacang merantau ke Padang menggunakan kereta.
Radjab, dalam Semasa Kecil di Kampung, pernah mencatat tentang stasiun itu, juga tentang limaunya yang manis, juga tentang kampung Kacang itu sendiri. “Dari Solok kami menumpang kereta api ke Singkarak. Di sini turun dan berjalan kaki sampai di Kacang. Di sebuah lepau di kampung itu kami bermalam, sambil memakan jeruk kacang yang dikenal manis sepuas-puasnya,” katanya.
Sementara, tidak jauh dari Kacang, di stasiun Batu Tabal, tidak ada pesta. Hanya kesepian yang bergelayut di sepanjang rel. “Tidak ada lagi kereta,” kata Ermi, perempuan paruh baya. Rumahnya sejengkal dari rel stasiun Batu Tabal. Bangunan stasiun yang kini berfungsi sebagai warung kopi, tempat duduk ibu-ibu, saling bercerita. Kepada saya mereka bercerita tentang bagaimana masa kecil di sini, ketika gerbong-gerbong penuh batu bara lewat di stasiun ini. Kereta yang semula hanya berisi gerbong-gerbong batu bara, lantas ditambah dengan gerbong-gerbong penumpang yang berisi pedagang.
Seperti yang dicatat Radjab juga, lebih seratus tahun yang lalu, “Sedang makan, kami lihat di seberang danau itu berpuluh-puluh gerobak batu arang dari Batu Tebal menuju Singkarak, menyusur tepi danau sebelah timur, seperti seekor ular besar. Kami semua memandangi kereta itu sampai lenyap dari mata di Singkarak.”
Di stasiun lain, Padang Sibusuk, saya menemui Liswati (57 tahun) yang sedang membereskan rumahnya. Rumahnya adalah stasiun itu sendiri.
“Siang malam, kereta lewat. Masih ingat saya bunyinya,” katanya. Ketika era jaya kereta api, orang-orang mengantre menunggunya di stasiun Padang Sibusuk menuju Muaro Sijunjung, dari Muaro Sijunjung ada yang ke Solok, atau ke Sawahlunto. “Saya tinggal di gedung stasiun ini. Siapa lagi yang mau menempati? Ayah saya mandor batu bara di kereta, kakek saya penjaga kereta kemudian dipaksa Jepang jadi romusha dan tidak pernah kembali, semua keluarga saya pekerja untuk batu bara dan kereta,” katanya, bangga, sekaligus pilu. Dari kecil hingga kini, usianya telah lewat paruh baya, ia begitu dekat dengan kereta. Hanya saja, kereta tidak lagi melintas. Namun, hidupnya tidak berbeda jauh dari kereta api, atau dari stasiun yang tidak lagi digunakan, yang telah somplak di sana-sini dan kondisinya mengenaskan ini. Ia hidup bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya.
Meninggalkan Liswati, saya telah memasuki Silungkang, daerah kecil di pinggir Kota Sawahlunto yang dicatat dengan tinta merah sebagai pusat pemberontakan yang diprakarsai oleh orang dari lintas etnis, utamanya dari orang-orang tambang. Di Silungkang pula, tersebar pusat-pusat kerajinan yang terkenal sampai ke Eropa; tenun yang memiliki corak dan warna yang beragam seakan menggambarkan pluralitas masyarakatnya.
***
Saya tiba di Sawahlunto kembali. Saya tidak lagi menemui Sudarma. Ia sudah wafat dan rumah Fak Sin Kek masih diam membisu di tengah kota. Saya bergegas menuju Puncak Cemara, melihat Sawahlunto dari atas: rumah-rumah berjejer rapi, besi-besi raksasa yang menyangga lingkaran beton, bekas-bekas pabrik yang ditinggalkan, juga pasar-pasar yang ramai pada hari-hari tertentu. Dari puncak ini, Sawahlunto terlihat seperti sebuah miniatur kota tambang yang tertutup kabut. Matahari sebentar lagi akan tenggelam dari balik bukit. Di tempat saya berdiri ini dulu noni-noni Belanda berselunjur melihat petang yang rembang, dan langit menyemburatkan warna jingga. Di bawah sana, para pekerja, lori dan kereta silih berganti mengeluarkan batu bara dan menaruhnya di gerbong-gerbong yang parkir di stasiun.
Stasiun itu sekarang disempurnakan menjadi museum kereta api yang memajang foto-foto, miniatur gerbong dan lokomotif uap. Di samping museum, sebuah gerbong dan lokomotif ditaruh penuh perawatan, lokomotif E1060 yang kerap disebut Mak Itam. Lokomotif uap terakhir pengangkut gerbong-gerbong batu bara penyuplai bahan bakar yang menggerakkan mesin-mesin industri di dunia itu seperti menunggu lapuk tapi juga menolak digerogoti usia.
Sirine milik perusahaan tambang berdengung di ujung November 2023 yang murung. Tepat tengah hari pada jam tua di puncak menara kantor perusahaan tambang terbesar di Sumatra pada abad lalu. Sirine penanda jam istirahat bagi para pekerja, yang sekarang hanya tersisa puluhan orang saja dari beribu-ribu banyaknya dulu. Suaranya yang panjang berpendar ke seantero kota, menjalar ke pucuk-pucuk pinus di perbukitan, seperti hendak menjagakan masa silam yang terkantuk-kantuk dan beku. Perbukitan yang berbaris, bagai kuli-kuli paksa di abad lampau, melingkari pusat kota kecil bentukan Belanda ini. Kota yang dulunya hanya sehamparan sawah di tengah cekungan lembah datar yang dialiri Sungai Lunto.
Azan zuhur dari menara masjid di pusat kota merambat perlahan. Masa lalu menghamburkan dirinya. Dulu, menara mesjid itu adalah cerobong asap dari pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara yang dari sana listrik menerangi sekujur Sawahlunto dengan cahaya. Tapi kini, setelah pembangkit listrik itu tidak lagi beroperasi, di puncak cerobong asap itu kemudian diletakkan corong pengeras suara milik masjid raya terbesar di kota itu.
Cholid Sutawikarta sedang duduk bersantai di rumahnya di tengah kota. Saya mengunjunginya setelah jeda siang. Ia pensiunan masinis kereta api yang membawahi dua pasang juru langsir. Sekali waktu, lututnya pernah dihantam pinggir kereta. Sekarang, giginya telah palsu semua.
“Siang-malam bunyi terompet dan peluit terdengar ke kamar tidur. Sebanyak 25 ton batu bara tiap gerbong, sekali jalan sepuluh gerbong, ada dua lokomotif yang mendorong. Tiap satu jam, kereta akan berbunyi, suara rodanya, peluitnya, o..” kata Cholid mengenang Sawahlunto, kota tempat ia hidup hingga usianya sudah 75 tahun kini. “Kaki saya pernah ditabrak kereta,” kata Cholid, mengulangi apa yang tadi juga sudah disebutnya.
Cholid masih bisa membayangkan bagaimana kehidupan kota kecil bentukan kolonial itu. Saat batu bara masih dikeruk dan kereta yang mengangkutnya tiap dua jam sekali membunyikan terompet, suaranya menggema ke seantero kota.
Suatu ketika, ia melihat gadis penjual kerupuk yang tiap hari naik gerbong ke Solok dan pulang lagi ke Sawahlunto padasore hari. Mukanya memerah. Cholid begitu bersemangat bercerita. Gadis yang hampir tiap hari ia lihat turun naik gerbong dari Sawahlunto ke Muaro Kalaban itu membuat Cholid muda gundah. Gadis penjual kerupuk itu menjadi istri Cholid kemudian.
Pada gerbong-gerbong batu bara, ia dan ribuan pekerja menyandarkan nasib. Dan dalam gerbong-gerbong kereta juga ia menemukan cinta. Kini, ketika ia tidak lagi bekerja mengatur laju kereta dan istrinya telah wafat beberapa tahun silam, kerupuk masih bertumpuk-tumpuk di rumahnya. Ia sendiri yang memproduksi kerupuk. Hanya saja, kerupuk itu tidak dibawa lagi oleh kereta.
“Kehidupan pahit. Saya pensiun dini tahun 2000. PT. Ombilin seperti telah bangkrut saja. Sejak 2005, kereta berhenti. Batu bara sudah tidak ada. Orang sudah membeli motor, mobil banyak,” kata Cholid sembari membenarkan letak gigi palsunya.
Kini, kereta sudah lama tidak lagi mendengus di Sawahlunto. Dan perempuan itu, yang kemudian mendampingi hidup Cholid selama puluhan tahun, juga telah mangkat. Sawahlunto menjadi kota yang berbeda bagi Cholid sekarang.
“850 rupiah sebulan, ketika itu satu emas (2,5 gram) pas 850 rupiah,” ia mengenang bagaimana gajinya ketika bekerja sebagai PPKA atau Petugas Perjalanan Kereta Api. Di rumahnya banyak kerupuk ubi bertumpuk. Apa sekarang ia mengubah profesi menjadi penjual kerupuk ubi?
Cholid tersenyum. Mukanya memerah. Ia kuatkan lagi gigi palsunya, dan ia membawakan air minum buat saya dan kemudian melanjutkan ceritanya.
Tidak jauh dari rumah Cholid, Bukhari duduk menatap ke perbukitan di belakang rumahnya. Di kaki perbukitan itu, rel membentang menuju lubang kalam, terowongan gelap. Di sisi rel sebelum terowongan, Bahar Lelo Sutan, ayah Bukhari berkubur.
“Teman saya Jono baru diangkat jadi masinis, ia berdoa dulu di kuburan bapak saya. Mungkin begitu cara orang Jawa minta berkat. Bapak saya masinis batu bara, dari kecil saya sudah dibawa naik kereta,” kata Bukhari.
Ketika Sawahlunto ingin mengingat sejarahnya kembali lewat pariwisata, lokomotif uap yang telah dibawa ke Ambarawa, dibawa kembali balik ke Sawahlunto, tempat asalnya, tempat ia dulu dioperasikan. “ Saya yang ikut menjemputnya belasan tahun silam,” kata Bukhari.
“Lokomotif yang dinamai Mak Itam itu begitu susah diangkut. Kontainer yang mengangkutnya selalu bocor ban. Ini serius. Lok itu telah melindas selendang penari ronggeng,” kata Bukhari dengan mimik serius.
Cerita tentang ronggeng atau penari tandak, memang mengandung aroma seksualitas dan magis sekaligus. Termasuk kesialan bagi kontainer yang mengangkut Mak Itam?
***
Silo Gunung di pangkal Teluk Bayur, di masa jaya, tentulah terisi penuh dengan batu bara. Sebab ke sanalah semua produksi batu bara di Sawahlunto dikumpulkan, untuk kemudian dipindahkan ke perut kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan, dan dibawa jauh ke tempat mesin-mesin industri bekerja. Kereta api dengan gerobak-gerobak berisi batu bara tentu juga akan berseliweran lewat di situ. Suara mesinnya yang keras, juga peluitnya, dan dengus kepulan asapnya, akan membuat suasana ramai dan ribut. Begitupun para pekerja akan terlihat sibuklah mereka mengatur segalanya, dengan perkakas-perkakas yang terus berdentangan.
Tapi, kalau kini hendak disebut, semata kosong dan sepi saja yang terasa. Zaman kejayaan batu bara telah jauh berangkat, tapi apa yang ditinggal ada dalam keabadiannya. Di Stasiun-stasiun yang telah ditinggalkan, orang-orang mengenang lagi bagaimana batu bara, jalur-jalur kereta, dan bermuara ke sini, ke Teluk Bayur.
Saya tidak mau lebih berlama-lama di Silo Gunung. Tempat ini terlihat agak mengerikan ketika senja membayang. Hantu-hantu dari masa silam mungkin masih bergayut di tiang-tiang? Hantu-hantu kolonial yang sudah harus diusir.
Referensi :
Amran, Rusli. (1981). Sumatra Barat hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
Arsya, Deddy. (2017). Mendisiplinkan Kawula Jajahan: politik penjara Hindia Belanda abad XIX dan XX. Yogyakarta: Labirin.
Asoka, Andi, dkk. (2005). Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok: Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Padang: LPTIK Universitas Andalas.
Colombijn, Freek. (2005). A Moving History of Middle Sumatra, 1600-1870. Leiden: KITLV.
Erman, Erwiza. (1999). Miners, managers and the state: A socio-political history of the Ombilin coal-mines, West Sumatra, 1892-1996. Thesis : Universiteit van Amsterdam.
Hendrik de Greve, Willem (1871). Het Ombilien Kolenveld in de Padangsche Bovenlanden en Het Transportstelsel op Sumatra’s Westkust.
Hubert van Kol, Henri. (1903). Uit onze koloniën: Uitvoerig reisverhaal. Leiden: A.W. Sijthoff.
Radjab, Muhamad. (2019). Semasa Kecil di Kampung. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Rodgers, Susan. (2005). “A Nederlander woman’s recollections of colonial and wartime Sumatra: from Sawahlunto to Bangkinang internment camp.” Indonesia,Vol. 79.
Rusli, Marah. (2008). Sitti Nurbaya: Kasih tak sampai. Jakarta: Balai Pustaka.
Syafril, Elsa.P.E. (2011). Menggali Bara, Menemu Bahasa: Bahasa Tansi, Bahasa Kreol Buruh dari Sawahlunto. Sawahlunto: Pemerintah Kota Sawahlunto.
Zubir, Zaiyardam. (2006). Pertempuran nan tak kunjung usai: eksploitasi buruh tambang batubara Ombilin oleh colonial Belanda 1891-1927. Padang: Andalas University Press.



